Samudra Ambisi: Mengurai Visi dan Realita Ekonomi Biru Indonesia
- Roni Adi
- Aug 30, 2025
- 7 min read
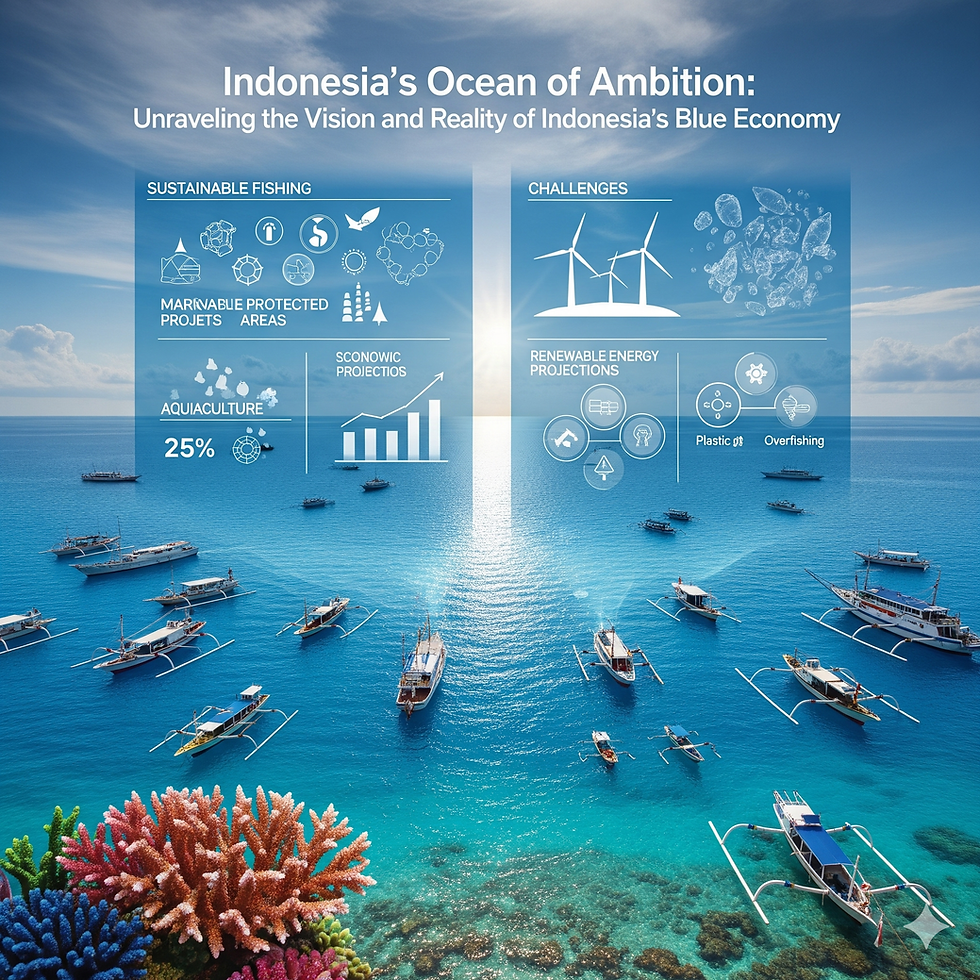
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, takdir Indonesia terukir di atas lautan. Laut bukanlah sekadar hamparan biru yang memisahkan pulau, melainkan urat nadi kehidupan, sumber pangan, dan panggung sejarah bangsa. Menyadari potensi raksasa yang terkandung di dalamnya, pemerintah Indonesia secara resmi menempatkan "Ekonomi Biru" sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan jangka panjangnya. Visinya begitu megah: mengubah sumber daya laut dan pesisir yang melimpah menjadi mesin penggerak ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Namun, di antara cita-cita besar dan kenyataan di lapangan, terbentang samudra tantangan yang kompleks. Indonesia telah merancang sebuah kerangka kebijakan yang canggih, lengkap dengan peta jalan yang detail menuju tahun 2045. Akan tetapi, perjalanan untuk mewujudkan mimpi ini tidaklah mulus. Artikel ini akan membawa kita menyelami lebih dalam, mengurai benang-benang visi, kebijakan, dan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam menavigasi samudra ambisinya.
Panggilan Samudra, dari Konsep Global Menjadi Jati Diri Bangsa
Gagasan "Ekonomi Biru" mulai bergaung di panggung dunia sekitar tahun 2009 dan menjadi topik hangat dalam pertemuan global Rio+20 pada 2012. Intinya sederhana namun mendasar: kita harus berhenti melihat laut hanya sebagai tempat untuk mengeruk kekayaan (ekonomi laut) dan beralih ke model yang lebih cerdas. Model ini menekankan inovasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan lautan kita tetap sehat untuk generasi mendatang.
Bagi Indonesia, sebuah bangsa yang 70% wilayahnya adalah air dan memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia, konsep ini ibarat gayung bersambut. Laut adalah sumber makanan, mata pencaharian, dan pendapatan negara yang tak ternilai. Pemerintah Indonesia dengan cepat menangkap peluang ini, melihatnya sebagai cara untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan yang pada akhirnya akan menopang pembangunan ekonomi nasional.
Langkah ini menandai sebuah pergeseran paradigma yang krusial. Selama puluhan tahun, narasi tentang lautan Indonesia sering kali bernada defensif: memberantas pencurian ikan, menegaskan kedaulatan di perairan yang disengketakan, dan menjaga perbatasan maritim. Dengan memeluk ekonomi biru, Indonesia secara sadar mengubah cara pandangnya. Laut tidak lagi hanya dilihat sebagai wilayah yang harus dipertahankan, melainkan sebagai ekosistem dinamis yang dapat menjadi mesin baru untuk pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan.
Perubahan narasi ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah prasyarat penting untuk menarik investasi, kemitraan teknologi, dan talenta yang dibutuhkan untuk membuka sektor-sektor baru yang menjanjikan, seperti bioteknologi kelautan dan energi terbarukan dari laut.
Hebatnya, Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep ini untuk dirinya sendiri. Indonesia juga tampil sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia memperjuangkan definisi Ekonomi Biru yang lebih inklusif, yang tidak hanya mencakup lautan tetapi juga sumber daya air tawar di darat dengan pendekatan "dari hulu ke hilir" (source-to-sea). Langkah cerdas ini memastikan negara-negara ASEAN yang tidak memiliki laut, seperti Laos, dapat ikut serta, sehingga memperkuat persatuan regional. Ini menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan ekonomi dapat menjadi alat diplomasi yang canggih untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan.
Arsitektur Raksasa di Atas Kertas
Untuk mewujudkan ambisi besarnya, Indonesia tidak main-main. Pemerintah telah membangun arsitektur kebijakan yang kokoh, ditopang oleh dua dokumen strategis utama.
Pertama adalah Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesian Ocean Policy - IOP) yang terbit pada 2017. Anggaplah ini sebagai "konstitusi" atau cetak biru samudra Indonesia. Dokumen ini meletakkan visi besar dan kerangka kerja holistik untuk mengelola seluruh domain maritim negara, mencakup segala hal mulai dari pengembangan sumber daya manusia kelautan, keamanan maritim, tata kelola, hingga pembangunan ekonomi.
Kedua, dan yang menjadi panduan operasionalnya, adalahPeta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 (Indonesia Blue Economy Roadmap). Jika IOP adalah visinya, maka Peta Jalan ini adalah GPS-nya. Dokumen yang dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ini menguraikan langkah-langkah, program, dan target yang jelas untuk mencapai visi tersebut. Salah satu target utamanya sangat ambisius: meningkatkan kontribusi ekonomi biru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sekitar 8% menjadi 15% pada tahun 2045.
Untuk menjalankan rencana raksasa ini, ada beberapa "aktor" utama di pemerintahan:
BAPPENAS: Berperan sebagai "arsitek utama" yang merancang kerangka konseptual dan peta jalan jangka panjang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Bertindak sebagai "implementator utama" di lapangan, yang menerjemahkan strategi menjadi program nyata, seperti kebijakan perikanan berkelanjutan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves): Berfungsi sebagai "konduktor orkestra". Tugasnya sangat krusial namun sulit: memastikan semua kementerian terkait (KKP, Pariwisata, Keuangan, dll.) bekerja secara sinkron dan harmonis, tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di atas kertas, pembagian peran ini terlihat logis. Namun, di sinilah letak salah satu tantangan terbesar. Pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat oleh apa yang disebut sebagai "labirin institusional". Banyak analisis menunjukkan adanya "manajemen laut yang terfragmentasi", "tumpang tindih kewenangan" antar lembaga, dan "kolaborasi antar-kementerian yang tidak memadai". Kemenko Marves pada periode pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tugas berat untuk membongkar silo-silo ego sektoral yang telah mengakar kuat. Kegagalan dalam koordinasi ini bisa menjadi titik kegagalan utama yang menghambat seluruh agenda ekonomi biru, secanggih apa pun rencana yang telah dibuat.
Mesin Penggerak Ekonomi Biru: Peluang dan Paradoks
Untuk memahami bagaimana ekonomi biru ini bekerja dalam praktiknya, mari kita selami beberapa sektor utamanya, di mana peluang besar sering kali diiringi oleh paradoks yang tak terduga.
Perikanan Berkelanjutan: Modernisasi vs. Inklusivitas Pemerintah meluncurkan program andalan yang disebut Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Logikanya adalah beralih dari mengontrol jumlah kapal yang boleh melaut, menjadi mengontrol total ikan yang boleh ditangkap. Sistem ini didukung oleh teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal untuk memastikan kepatuhan.
Namun, di sinilah sebuah paradoks muncul. Sistem yang canggih dan terpusat ini dikhawatirkan akan lebih menguntungkan armada industri skala besar yang mampu membeli teknologi dan menavigasi birokrasi yang rumit. Hal ini berisiko menyingkirkan nelayan-nelayan kecil, yang jumlahnya mencapai 96% dari total nelayan di Indonesia, dari wilayah tangkapan tradisional mereka.
Di saat yang sama, ada program lain yang disebut Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang bertujuan untuk memodernisasi 1.100 desa pesisir dengan fasilitas seperti dermaga modern dan tempat penyimpanan dingin (cold storage). Tujuannya mulia, yaitu memberdayakan masyarakat lokal. Akan tetapi, ada skenario yang mungkin terjadi di mana kampung-kampung yang baru dimodernisasi ini justru menjadi pusat layanan yang lebih efisien bagi armada-armada industri besar yang diuntungkan oleh kebijakan kuota. Akibatnya, dua kebijakan andalan ini bisa jadi bekerja saling bertentangan: yang satu memusatkan kekuatan ekonomi, sementara yang lain memodernisasi ruang fisik di mana kekuatan itu dieksekusikan.
Konservasi Laut: Antara Target Luas dan Realita "Taman Kertas" Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Areas - MPAs). Targetnya adalah melindungi 32,5 juta hektar wilayah laut pada tahun 2030, dan saat ini sudah mendekati angka 28,4 juta hektar.
Tantangannya bukan lagi pada penetapan batas di atas peta, melainkan pada efektivitas pengelolaan di lapangan. Tanpa pendanaan yang cukup untuk patroli, pengawasan, dan pelibatan masyarakat, kawasan konservasi ini berisiko menjadi "taman kertas" (paper parks)—indah di atas kertas, tetapi kosong dari perlindungan nyata. Laporan dari lapangan, bahkan dari lokasi yang sudah mapan, menunjukkan adanya tantangan seperti "sumber daya pemantauan yang tidak memadai". Ini adalah celah kritis antara kebijakan penetapan dan realitas implementasi.
Jurang Finansial: Uang Besar dan Pengusaha Kecil yang Terlupakan
Potensi ekonomi dari lautan Indonesia sungguh mencengangkan, dengan nilai yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari US$1,3 triliun. Untuk menggerakkan potensi ini, dibutuhkan modal yang sangat besar. Di sini, kita melihat sebuah jurang yang memisahkan dua dunia finansial yang berbeda.
Di satu sisi, di level makro, segalanya tampak bergerak maju. Pemerintah aktif mengembangkan mekanisme "Keuangan Biru" (Blue Finance) yang canggih, seperti obligasi biru (Blue Bonds) untuk menarik investasi besar. Proyek-proyek skala besar juga didanai oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, contohnya adalah proyek LAUTRA senilai US$210 juta untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan mata pencaharian masyarakat pesisir di Indonesia Timur.
Namun, di sisi lain, di level mikro, ceritanya sangat berbeda. Tulang punggung ekonomi pesisir adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—mulai dari nelayan kecil, petani rumput laut, hingga operator wisata lokal. Kontribusi mereka terhadap PDB nasional lebih dari 61% dan mereka menyerap 97% tenaga kerja domestik. Ironisnya, meskipun peran mereka sangat vital, mereka adalah pihak yang paling kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal.
Hambatan utamanya adalah persyaratan agunan fisik (seperti sertifikat tanah) yang diminta oleh bank. Seorang nelayan kecil tentu sering kali tidak memiliki aset seperti itu. Akibatnya, terciptalah sebuah "celah di tengah yang hilang" (missing middle) dalam arsitektur keuangan biru Indonesia. Ada aktivitas finansial yang canggih di tingkat atas, sementara di tingkat bawah, para pelaku utama ekonomi biru justru terkurung di luar sistem keuangan formal. Tanpa solusi pembiayaan yang dirancang khusus untuk mereka, ekonomi biru berisiko menjadi model ekonomi yang berat di atas, yang hanya menguntungkan pemerintah dan korporasi besar, sementara gagal mengangkat kesejahteraan komunitas pesisir yang seharusnya menjadi sasaran utamanya.
Suara dari Pesisir: Antara Pemberdayaan dan Peminggiran
Secara prinsip, kerangka ekonomi biru dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan manfaat sumber daya laut terdistribusi secara adil. Namun, banyak laporan dari lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita ini dengan kenyataan.
Organisasi masyarakat sipil telah memperingatkan bahwa implementasi proyek-proyek ekonomi biru sering kali berisiko menggusur komunitas lokal dan mengganggu mata pencaharian tradisional mereka. Proyek infrastruktur skala besar, yang sering kali dibenarkan atas nama ekonomi biru, dapat berujung pada "perampasan tanah atas nama pariwisata" atau pengembangan industri, yang memaksa komunitas nelayan meninggalkan tanah leluhur mereka.
Kisah dari Pulau Lombok menjadi studi kasus yang kuat tentang "paradoks kemakmuran". Lombok dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari mutiara, rumput laut, perikanan, hingga pariwisata bahari. Pulau ini bahkan pernah menjadi proyek percontohan pengembangan ekonomi biru. Namun, ironisnya, Lombok tetap menjadi salah satu "kantong kemiskinan" di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi terkonsentrasi di komunitas pesisirnya.
Mengapa ini terjadi? Penelitian menunjukkan bahwa potensi besar itu gagal mengangkat masyarakat dari kemiskinan karena beberapa kegagalan sistemik: kurangnya akses modal bagi masyarakat lokal, kesenjangan keterampilan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan tata kelola pemerintahan yang lemah. Kasus Lombok adalah bukti nyata bahwa sekadar memiliki sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Menjembatani Samudra Ambisi dan Realita
Tidak diragukan lagi, Indonesia telah berhasil membangun sebuah visi kelas dunia dengan arsitektur kebijakan yang komprehensif untuk ekonomi birunya. Ambisi untuk mengubah lautan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan, adil, dan tangguh telah tertanam kuat dalam strategi nasional.
Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar kini bukanlah lagi soal perumusan visi, melainkan soal eksekusi. Keberhasilan Indonesia akan bergantung pada kemampuannya untuk menjembatani beberapa kesenjangan kritis:
Kesenjangan antara kebijakan dan tata kelola, di mana strategi yang baik dilemahkan oleh koordinasi yang buruk antar kementerian.
Kesenjangan antara modernisasi dan inklusivitas, di mana kebijakan berisiko menguntungkan pemain besar dan meminggirkan nelayan kecil.
Kesenjangan antara keuangan makro dan usaha mikro, di mana instrumen keuangan canggih gagal menjangkau para pengusaha kecil yang paling membutuhkannya.
Kesenjangan antara pertumbuhan PDB dan keberlanjutan sejati, di mana fokus pada angka pertumbuhan berisiko mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan nyata di lapangan ini, Indonesia dapat menavigasi perairan yang kompleks di hadapannya. Hanya dengan begitu, samudra ambisi yang luas ini dapat diubah menjadi sumber kemakmuran dan keberlanjutan yang nyata, bukan hanya untuk negara, tetapi untuk setiap insan yang menggantungkan hidupnya pada lautan Nusantara.



Comments